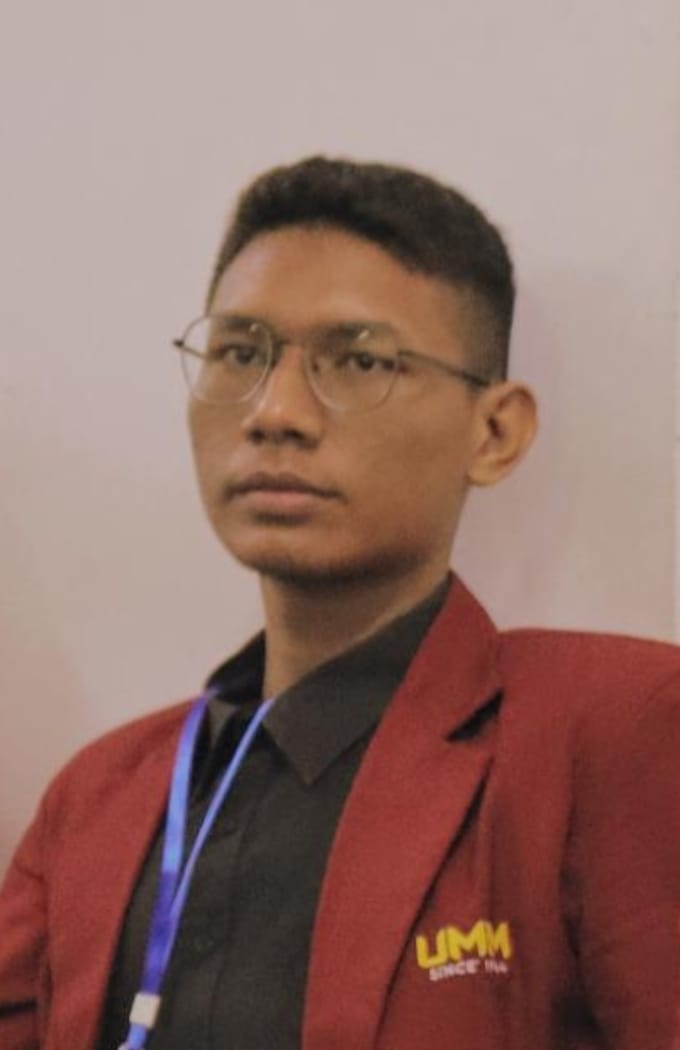
Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia masih menjadi tantangan utama hingga kini, terutama di kawasan-kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar atau yang dikenal dengan istilah wilayah 3T. Ketimpangan ini tidak hanya terkait dengan minimnya infrastruktur dan layanan dasar, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap lapangan kerja yang memadai. Sementara pusat-pusat pertumbuhan seperti Jawa dan Sumatra terus berkembang dan menyerap banyak tenaga kerja, daerah 3T kerap tertinggal akibat keterbatasan fasilitas, rendahnya mutu pendidikan dan pelatihan kerja, serta kurangnya investasi di bidang ketenagakerjaan.
Data
Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di
banyak wilayah 3T masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Di sisi
lain, laju urbanisasi yang terus meningkat menyebabkan terjadinya penumpukan
tenaga kerja di kota-kota besar, yang pada akhirnya menimbulkan persaingan
kerja yang semakin ketat dan munculnya berbagai persoalan sosial. Hal ini
menunjukkan perlunya pemerataan distribusi tenaga kerja ke seluruh wilayah,
termasuk kawasan 3T yang sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam dan
manusia yang besar namun belum terkelola secara optimal. Pemerintah melalui
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes
PDTT), bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, telah meluncurkan berbagai
program seperti pelatihan kerja berbasis desa, program padat karya, hingga
penguatan balai latihan kerja (BLK) komunitas. Namun, implementasi
program-program ini masih memerlukan penguatan melalui strategi yang lebih
relevan dengan konteks lokal.
Penyediaan
tenaga kerja yang inklusif di wilayah 3T bukan semata-mata soal memindahkan
sumber daya manusia, melainkan membangun sistem ketenagakerjaan yang
kontekstual dan berkelanjutan. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan antara
lain adalah pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi lokal.
Di Papua, misalnya, pelatihan dapat difokuskan pada pengelolaan sagu dan
pariwisata berbasis alam, sedangkan di Nusa Tenggara bisa diarahkan pada sektor
peternakan dan kerajinan seperti tenun. Selain itu, penguatan infrastruktur
digital juga menjadi langkah penting agar masyarakat di wilayah 3T dapat
mengakses peluang kerja secara daring, seperti ekonomi digital dan usaha mikro
berbasis internet. Dunia usaha pun perlu dilibatkan melalui kemitraan antara
pemerintah dan swasta, baik lewat program tanggung jawab sosial perusahaan
(CSR), penyediaan pelatihan kerja, maupun investasi di sektor produktif lokal.
Kemitraan ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja
baru yang sesuai dengan potensi setempat. Selain itu, pendekatan transmigrasi
juga perlu diperbaharui dengan model relokasi berbasis keterampilan, di mana
tenaga kerja yang memiliki kompetensi tertentu dapat diberdayakan untuk tinggal
dan bekerja di wilayah 3T, tentunya dengan dukungan insentif yang layak serta
jaminan sosial yang memadai.
Mewujudkan masa depan yang adil dan inklusif berarti memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Upaya penyediaan tenaga kerja di wilayah 3T bukan hanya menjadi bagian dari strategi menurunkan angka pengangguran secara nasional, tetapi juga sebagai bentuk nyata dari pemerataan pembangunan. Dengan pendekatan yang berbasis pada potensi lokal, dukungan lintas sektor, serta penguatan kapasitas masyarakat, maka kemajuan wilayah tertinggal bukan hanya menjadi harapan, melainkan kenyataan yang dapat diwujudkan secara berkelanjutan. (Oleh: Moh. Raihan Nur Islami|Ekonomi Pembangunan|Universitas Muhammadiyah Malang)
Pesisir Utara gang 7, Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo, Jawa Timur
+6282222211086
admin@kontripantura.com
©2025 Kontri Pantura. All Rights
Reserved.
Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon